 Jakarta, KompasOtomotif
Jakarta, KompasOtomotif – Dyonisius Beti termasuk
orang sukses di masa muda. Saat usianya baru menginjak 34 tahun, anak
pedagang karet dari Jambi itu langsung dipercaya menjabat sebagai
Direktur Pemasaran di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Dyon
dipercaya mampu mewakili keinginan Yamaha Jepang untuk memasukkan
ide-ide segar dari anak muda lokal.
Namun sayang, saat
semangatnya menggebu untuk memajukan perusahaan, situasi ekonomi di
Indonesia turun drastis akibat gejolak pada 1998 sampai dilanda krisis
moneter. Nilai tukar rupiah terjun bebas, dari Rp 2.500 per 1 dollar AS
sampai puncaknya mencapai Rp 17.000 per 1 dollar AS. Bunga bank pun naik
menjadi 5 persen.
”Saya bergabung tahun 1996, tau-tau krisis
mulai 1998-1999. Permintaan turun jauh, dari 1,7 juta unit menjadi hanya
400.000 unit Dollar atau tinggal 20 persennya saja. Setiap unit yang
kami jual saat itu rugi, perusahaan pun kolaps,” kenang Dyon.
Dua kunciPada
masa ini, ada dua hal yang dia ingat. Baginya, perusahaan boleh rugi
dan produksi bisa minim. Tapi, pabrik tak boleh tutup. Lulusan Teknik
Sipil ITB itu berpendapat, sekali tutup, kepercayaan masyarakat hilang.
”Karena masyarakat sudah beli jutaan produk Yamaha. Kalau
dealer
gak bisa suplai, bagaimana mereka lanjutkan bisnis? Mau servis gimana?
Fokusnya saat itu, pikirkan konsumen. Mati hidup kita tergantung
konsumen. Kalau kita khianati, besok-besok balik lagi udah
nggak percaya. Itulah kenapa, kami jaga, tetep produksi dan terbatas, tapi
aftersales harus jalan,” beber Dyon.
Hal lain yang dianggap penting saat itu adalah menjaga merek, karena sudah dibangun dengan susah payah.
Brand
atau merek dianggap sangat mahal, namun tak terlihat wujudnya. Sesuatu
yang baru meski pemodalnya kuat, belum tentu bisa berjalan mulus.
KompasOtomotif-donny apriliananda Dyonisius Beti harus melalui perjalanan berliku sebelum memimpin Yamaha Indonesia.
”Flashback”Semua teori itu ternyata tak didapatnya secara otodidak. Dyon lantas
flashback,
mengenang saat dirinya menimba ilmu pemasaran dengan kuliah S-2 sebagai
angkatan pertama Magister Management (MM) Universitas Indonesia (UI),
tahun 1989-1990, saat dirinya pertama diterima kerja seusai lulus dari
ITB.
Baginya, bekal dari Teknik Sipil tak cukup. ”Saya melihat
kekurangan saya. Teknik analisa lebih unggul, tapi kepekaan bisnis jelas
kurang. Ini harus diasah dan digabung,” ujar Dyon.
Selama kuliah
S-2 sembari kerja, Dyon ditempa masa sulit. Dirinya harus pandai-pandai
mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas kuliah hingga menyiapkan diri
kembali segar saat ngantor. Dua tahun ”sengsara”, akhirnya lulus juga.
Diam adalah keputusanKembali
ke rumitnya permasalahan perusahaan saat itu, Dyon mendapatkan
pelajaran baru yang tak pernah dia duga. Di saat mengalami masa-masa
paling kritikal, penjualan turun dan perusahaan rugi, semangat muda Dyon
sangat berapi untuk segera keluar dari ”lingkaran panas”.
Dia
tak tahan karena penjualan begitu kecil dan berusaha mencari jalan
keluar. Semangat muda itu pun akhirnya diredam oleh nasihat dari orang
Jepang yang saat itu menjadi senior di Yamaha.
”Saya belajar dari
senior saya, Mr Nakajima. Suatu saat dia meminta saya ikut main golf
sembari mencari jalan keluar. Di sana saya hanya menemaninya, karena
tidak bisa. Setelah selesai, ya sudah, itu saja. Lalu apa kesimpulannya?
Saya tidak mengerti,” cerita Dyon lantas tertawa.
Ternyata, dari
situ Dyon belajar bahwa tidak melakukan apa-apa juga termasuk keputusan
penting sebagai jalan keluar. ”Saat krismon dan susah itu, produksi
banyak rugi, jual lebih banyak enggak bisa, daya beli susah.
You harus tunggu,” ucap Dyon.
Kadang-kadang,
lanjutnya, kita tidak tahan dalam suatu tekanan. Saat terjepit, banyak
manusia berontak. Namun, analisa Mr Nakajima saat itu yang diserap Dyon,
kondisi negara yang kacau, Presiden Soeharto belum
clear turun atau bertahan,
decision-nya adalah
stay, diam, atau menunggu.
Lalu, keputusan apa lagi yang diambil Dyon untuk membangkitkan Yamaha dari keterpurukan? Tunggu kisah selanjutnya.
sumber;kompas
 MUENCHEN, KOMPAS.com —
Gelandang Bayern Muenchen, Franck Ribery, mengaku tidak peduli apakah
bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, bakal menghadiri malam
penganugerahan FIFA Ballon d'Or 2013 atau tidak.
MUENCHEN, KOMPAS.com —
Gelandang Bayern Muenchen, Franck Ribery, mengaku tidak peduli apakah
bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, bakal menghadiri malam
penganugerahan FIFA Ballon d'Or 2013 atau tidak. 








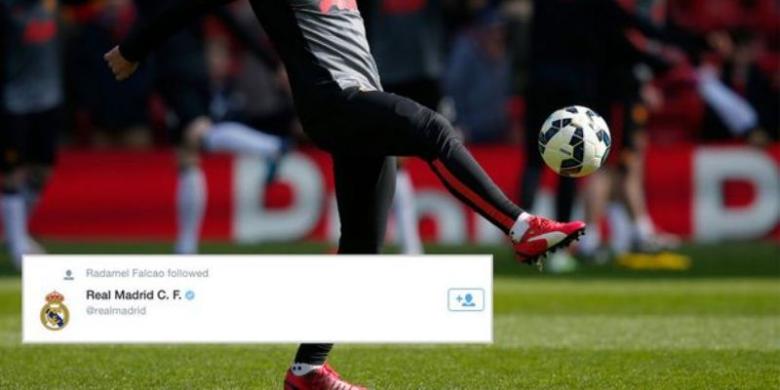








 Jakarta, KompasOtomotif – Banyak cara untuk menjadi
perhatian, termasuk salah satunya aktivitas yang dilakukan Yamaha DDS
Jakarta demi memasyarakatkan Mio M3 125. Kekuatan salah satu skutik
terbaru itu dibuktikan dengan menarik truk sepanjang 300-500 meter dalam
payung Yamaha Family Day di aktivitas ”Uji Kekuatan Mio M3 Attack
Kampung”.
Jakarta, KompasOtomotif – Banyak cara untuk menjadi
perhatian, termasuk salah satunya aktivitas yang dilakukan Yamaha DDS
Jakarta demi memasyarakatkan Mio M3 125. Kekuatan salah satu skutik
terbaru itu dibuktikan dengan menarik truk sepanjang 300-500 meter dalam
payung Yamaha Family Day di aktivitas ”Uji Kekuatan Mio M3 Attack
Kampung”. Jakarta, KompasOtomotif – Dyonisius Beti termasuk
orang sukses di masa muda. Saat usianya baru menginjak 34 tahun, anak
pedagang karet dari Jambi itu langsung dipercaya menjabat sebagai
Direktur Pemasaran di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Dyon
dipercaya mampu mewakili keinginan Yamaha Jepang untuk memasukkan
ide-ide segar dari anak muda lokal.
Jakarta, KompasOtomotif – Dyonisius Beti termasuk
orang sukses di masa muda. Saat usianya baru menginjak 34 tahun, anak
pedagang karet dari Jambi itu langsung dipercaya menjabat sebagai
Direktur Pemasaran di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Dyon
dipercaya mampu mewakili keinginan Yamaha Jepang untuk memasukkan
ide-ide segar dari anak muda lokal. Maranello, KompasOtomotif – Bos Ferrari, Luca di Montezemolo, meluapkan kekecewaan terhadap penyelenggaraan F1 yang dianggap tak lagi “greget”.
Pernyataan itu keluar sembari mengangkat kemungkinan, Ferrari akan
masuk ke level balapan yang lebih rendah, di ranah mobil sport.
“F1 tidak lagi bekerja. Pamornya menurun sebab Federation
International d'Automobile (FIA) telah melupakan bahwa orang-orang
menyaksikan balapan untuk kesenangan. Tidak ada yang ingin melihatnya
buat efisiensi, ayolah,” katanya seperti dilansir Wall Street Journal, pekan lalu.
Maranello, KompasOtomotif – Bos Ferrari, Luca di Montezemolo, meluapkan kekecewaan terhadap penyelenggaraan F1 yang dianggap tak lagi “greget”.
Pernyataan itu keluar sembari mengangkat kemungkinan, Ferrari akan
masuk ke level balapan yang lebih rendah, di ranah mobil sport.
“F1 tidak lagi bekerja. Pamornya menurun sebab Federation
International d'Automobile (FIA) telah melupakan bahwa orang-orang
menyaksikan balapan untuk kesenangan. Tidak ada yang ingin melihatnya
buat efisiensi, ayolah,” katanya seperti dilansir Wall Street Journal, pekan lalu.
 Paris, KompasOtomotif - Regulasi baru akan dilansir FIA
(Federation Internationale de l'Automobile) terkait balapan Formula 1.
FIA bakal melarang bentuk komunikasi melalui radio antara kru tim dan
pebalap.
Paris, KompasOtomotif - Regulasi baru akan dilansir FIA
(Federation Internationale de l'Automobile) terkait balapan Formula 1.
FIA bakal melarang bentuk komunikasi melalui radio antara kru tim dan
pebalap. Barcelona, KompasOtomotif - Pebalap McLaren, Fernando
Alonso, mengalami kecelakaan saat melakukan sesi tes pra-musim di
Sirkuit Catalunya, Spanyol. Akibat kecelakaan tersebut, Alonso sempat
dirawat intensif di rumah sakit.
Barcelona, KompasOtomotif - Pebalap McLaren, Fernando
Alonso, mengalami kecelakaan saat melakukan sesi tes pra-musim di
Sirkuit Catalunya, Spanyol. Akibat kecelakaan tersebut, Alonso sempat
dirawat intensif di rumah sakit. Paris, KompasOtomotif - FIA (Fédération Internationale
de l'Automobile) atau lembaga yang mengurusi perlombaan Formula 1,
merilis peraturan baru yang mengatur tentang perlengkapan pebalap. Kali
ini, FIA melarang pengubahan skema helm yang akan dipakai setiap
pebalap.
Paris, KompasOtomotif - FIA (Fédération Internationale
de l'Automobile) atau lembaga yang mengurusi perlombaan Formula 1,
merilis peraturan baru yang mengatur tentang perlengkapan pebalap. Kali
ini, FIA melarang pengubahan skema helm yang akan dipakai setiap
pebalap. Jakarta, KompasOtomotif - Garansindo Inter Global (GIG) akhirnya resmi meluncurkan merek asal Italia, dengan menjual hatchback
5-pintu Giuiletta di ajang IIMS 2014, Kamis (18/9/2014). Selain itu,
stan Alfa Romeo yang terletak di hall B, JIExpo, Kemayoran, Jakarta,
juga menampilkan mobil sport kompak 4C kupe.
Jakarta, KompasOtomotif - Garansindo Inter Global (GIG) akhirnya resmi meluncurkan merek asal Italia, dengan menjual hatchback
5-pintu Giuiletta di ajang IIMS 2014, Kamis (18/9/2014). Selain itu,
stan Alfa Romeo yang terletak di hall B, JIExpo, Kemayoran, Jakarta,
juga menampilkan mobil sport kompak 4C kupe.  Turin, KompasOtomotif — Audi sedang kebingungan mencari nama untuk SUV kompak entry level terbarunya.
Merek premium di bawah payung Grup VW ini enggan menggunakan nama "Q1"
untuk model barunya ini karena dianggap kurang sesuai dan mau memilih
"Q2". Masalahnya, nama Q2 sudah dipatenkan oleh Alfa Romeo di bawah
naungan Fiat Chrysler Automobile (FCA).
Turin, KompasOtomotif — Audi sedang kebingungan mencari nama untuk SUV kompak entry level terbarunya.
Merek premium di bawah payung Grup VW ini enggan menggunakan nama "Q1"
untuk model barunya ini karena dianggap kurang sesuai dan mau memilih
"Q2". Masalahnya, nama Q2 sudah dipatenkan oleh Alfa Romeo di bawah
naungan Fiat Chrysler Automobile (FCA). Turin, KompasOtomotif - Niatan Volkswagen Group buat
menguasai Alfa Romeo yang sudah dicanangkan dalam dua tahun terakhir
harus pupus. Fiat sebagai induk perusahaan menyatakan, Alfa Romeo tidak
dijual.
Turin, KompasOtomotif - Niatan Volkswagen Group buat
menguasai Alfa Romeo yang sudah dicanangkan dalam dua tahun terakhir
harus pupus. Fiat sebagai induk perusahaan menyatakan, Alfa Romeo tidak
dijual. Turin, KompasOtomotif – Alfa Romeo yang kini bernaung di bawah Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sedang ngebut mewujudkan ambisi menjadi merek yang kompetitif. Setelah mengumumkan target penjualan yang naik
Turin, KompasOtomotif – Alfa Romeo yang kini bernaung di bawah Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sedang ngebut mewujudkan ambisi menjadi merek yang kompetitif. Setelah mengumumkan target penjualan yang naik  Jakarta, KompasOtomotif – Produsen mobil asal Jerman,
BMW, memperkenalkan mobil pertamanya yang menggunakan penggerak roda
depan. Mobil dengan sebutan Active Tourer itu diluncurkan di Jakarta,
Kamis (26/3/2015).
Jakarta, KompasOtomotif – Produsen mobil asal Jerman,
BMW, memperkenalkan mobil pertamanya yang menggunakan penggerak roda
depan. Mobil dengan sebutan Active Tourer itu diluncurkan di Jakarta,
Kamis (26/3/2015). angerang, KompasOtomotif - Proton Holdings Berhad
sebagai produsen mobil asal Malaysia, sedang berupaya keras untuk bisa
bangkit dari keterpurukan baik di pasar negara sendiri, ataupun pasar
Asia termasuk Indonesia.
angerang, KompasOtomotif - Proton Holdings Berhad
sebagai produsen mobil asal Malaysia, sedang berupaya keras untuk bisa
bangkit dari keterpurukan baik di pasar negara sendiri, ataupun pasar
Asia termasuk Indonesia. ogor, KompasOtomotif - Setelah diperkenalkan pada IIMS
2014 September lalu, Renault Duster 4X4 akhirnya siap menjelajah medan
Indonesia. Kedatangan model ini cukup menarik, karena model tersebut
bermain sendiri di kelas small SUV yang menawarkan sistem gerak empat
roda.
ogor, KompasOtomotif - Setelah diperkenalkan pada IIMS
2014 September lalu, Renault Duster 4X4 akhirnya siap menjelajah medan
Indonesia. Kedatangan model ini cukup menarik, karena model tersebut
bermain sendiri di kelas small SUV yang menawarkan sistem gerak empat
roda. 

 JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengaku tidak dapat
memastikan apakah Prabowo Subianto akan menghadiri pelantikan presiden
dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang.
Hatta mengaku akan menanyakan langsung kepada Prabowo mengenai hal itu.
JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengaku tidak dapat
memastikan apakah Prabowo Subianto akan menghadiri pelantikan presiden
dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang.
Hatta mengaku akan menanyakan langsung kepada Prabowo mengenai hal itu.







 MELBOURNE – Secara resmi tim Manor Marussia akan
melewatkan seri pembuka Formula One (F1) 2015 di Sirkuit Albert Park,
Australia pada 15 Maret 2015. Hal ini terjadi setelah mereka banyak
menuai kendala di babak kualifikasi.
MELBOURNE – Secara resmi tim Manor Marussia akan
melewatkan seri pembuka Formula One (F1) 2015 di Sirkuit Albert Park,
Australia pada 15 Maret 2015. Hal ini terjadi setelah mereka banyak
menuai kendala di babak kualifikasi. VALENCIA – Performa gemilang Marc Marquez di pentas
MotoGP, diyakini akan terus menghadirkan ancaman bagi para pesaingnya.
Namun pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, merasa percaya bahwa rider Repsol Honda itu bukan merupakan hal yang mustahil untuk ditaklukkan
VALENCIA – Performa gemilang Marc Marquez di pentas
MotoGP, diyakini akan terus menghadirkan ancaman bagi para pesaingnya.
Namun pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, merasa percaya bahwa rider Repsol Honda itu bukan merupakan hal yang mustahil untuk ditaklukkan ALENCIA – Bukan rahasia lagi bila Spanyol disebut sebagai gudangnya pembalap-pembalap kelas dunia. Bahkan rider Drive
M7 Aspar, Nicky Hayden, menganggap Negeri Matador adalah tempat yang
sangat tepat untuk menimba ilmu bagi para pembalap muda asal Amerika
Serikat (AS).
ALENCIA – Bukan rahasia lagi bila Spanyol disebut sebagai gudangnya pembalap-pembalap kelas dunia. Bahkan rider Drive
M7 Aspar, Nicky Hayden, menganggap Negeri Matador adalah tempat yang
sangat tepat untuk menimba ilmu bagi para pembalap muda asal Amerika
Serikat (AS).
 BASEL – Habis sudah wakil Indonesia di ajang
bulutangkis Swiss Gold Grand Prix 2015. Harapan terakhir Indonesia di
semifinal, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang berada diunggulan pertama
mesti takluk dari pasangan Tiongkok, Liu Cheng/Bao Yixin 19-21 dan
19-21.
BASEL – Habis sudah wakil Indonesia di ajang
bulutangkis Swiss Gold Grand Prix 2015. Harapan terakhir Indonesia di
semifinal, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang berada diunggulan pertama
mesti takluk dari pasangan Tiongkok, Liu Cheng/Bao Yixin 19-21 dan
19-21. MELBOURNE – Pembalap Mercedes AMG, Nico Rosberg, kesal gagal meraih pole position
setelah dikalahkan rekan setimnya, Lewis Hamilton. Padahal, saat
menjalani sesi latihan bebas pertama dan kedua, pembalap asal Jerman
tersebut begitu digdaya menguasai balapan.
MELBOURNE – Pembalap Mercedes AMG, Nico Rosberg, kesal gagal meraih pole position
setelah dikalahkan rekan setimnya, Lewis Hamilton. Padahal, saat
menjalani sesi latihan bebas pertama dan kedua, pembalap asal Jerman
tersebut begitu digdaya menguasai balapan. MELBOURNE – Tampil dihadapan pendukungnya sendiri,
pembalap Red Bull Racing, Daniel Ricciardo gagal memberikan hasil
terbaik saat mentas di sesi kualifikasi Formula One (F1) yang diadakan
di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia.
MELBOURNE – Tampil dihadapan pendukungnya sendiri,
pembalap Red Bull Racing, Daniel Ricciardo gagal memberikan hasil
terbaik saat mentas di sesi kualifikasi Formula One (F1) yang diadakan
di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia.